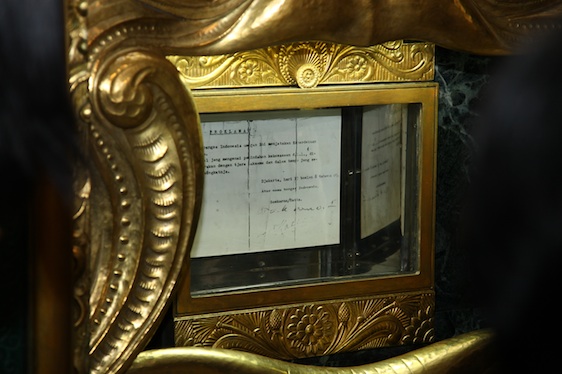Seorang pria tampak menampar wajahnya berulang-ulang sambil melafalkan bait-bait Injil (Lukas 12:3-11). Wajahnya perlahan-lahan tampak lebam, membengkak seiring dengan dirinya yang terengah-engah dan kepayahan melafalkan bait-bait tersebut. Mata berair dan liur yang terbersit di sudut mulutnya seolah meneriakkan sakit yang tak terperi. Selama kurang lebih 10 menit, ia ‘menghukum’ dirinya sendiri.
Adegan di atas adalah cukilan video What karya Reza Afisina yang diproduksi tahun 2001. Video performatif Reza yang kini menjadi koleksi Museum Guggenheim, New York, dianggap sebagai salah satu temuan penting dalam sejarah perkembangan seni video Indonesia.
Video What terpilih dalam kompilasi 10 tahun seni video Indonesia 2000 – 2010 terbitan ruangrupa. Kompilasi tersebut memuat 27 karya video yang dianggap penting dan menandai perkembangan video seni tanah air dalam kurun waktu satu dekade. Beberapa namaa lain yang juga masuk dalam kompilasi ini antara lain Ade Darmawan, Anggun Priambodo, Bagasworo Aryaningtyas, Hafiz, Mahadrika Yudha, Muhammad Akbar, Prilla Tania, Tintin Wulia, dan Wimo Ambala Bayang. Mereka masih konsisten berkarya hingga kini.
Membicarakan seni video tak bisa dilepaskan dari nama besar Nam June Paik. Seniman berkebangsaan Korea-Amerika ini diakui sebagai bapak video art. Ia mulai berkarya pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1965, menggunakan alat perekam video Portapak produksi Sony. Sejak itu ia semakin giat mengeksplorasi medium tersebut. Salah satu karya awalnya yang populer ialah TV Cello (1971). Paik menumpuk tiga buah televisi lengkap dengan leher dan senar cello. Masing-masing monitor menampilkan rekaman berbeda. “Television has been attacking us all our lives, now we can attack it back” selalu menjadi misi utamanya dalam berkarya. Kelahiran dan perkembangan seni video di Indonesia tentu saja tak serta-merta berangkat dari semangat yang sama dengan yang mendasari Paik dalam berkarya di era 1960-1970’an. Situasi di Amerika Serikat kala itu sangat berbeda dengan Indonesia, terutama perkembangan teknologinya.
“Television has been attacking us all our lives, now we can attack it back”
Kemajuan teknologi tersebut otomatis membuat negara-negara barat jauh di depan dengan menyelenggarakan festival-festival seni video dan seni media baru sejak lama. Seperti Brazil yang sudah tiga dekade menyelenggarakan festival Videobrasil. Ada pula Impakt Fetival yang diadakan di Utrecht, Belanda, sejak 1988, atau Images Festival yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1987 di Toronto, Kanada.
Perkembangan seni video Indonesia
Pada tahun 2001, ruangrupa, komunitas seni kontemporer berbasis di Jakarta, menggagas proyek Silent Forces, sebuah proyek seni video yang melibat seniman-seniman Indonesia dan internasional. Sebagai langkah awal, mereka melakukan riset mengenai penggunaan medium video dalam praktik seni rupa. Muncul beberapa nama besar seniman Indonesia yang menggunakan medium video dalam presentasi karya mereka, seperti Krisna Murti yang sudah bergelut dengan medium video sejak tahun 1980-an, Heri Dono yang membuat karya instalasi Hoping to Hear from You Soon (1992) dan Teguh Ostenrik yang pada sebuah pameran di Jakarta sekitar tahun 1994, menggunakan video sebagai medium berekspresi.
Nama Nerfita Primadewi juga mencuat karena aktif berkarya di pertengahan 1990-an, meski saat ini namanya tak terdengar lagi. Di luar nama-nama tadi, muncul temuan lain yang cukup menarik. Anak muda di pertengahan 1990-an aktif melakukan eksperimen video untuk kegiatan musik dan clubbing. Beberapa seniman bahkan diajak terlibat dalam eksperimentasi video ini.
Kegiatan-kegiatan yang mengetengahkan seni video dan seni media baru (new media arts) baru muncul pada awal 2000. Di Bandung, salah satu komunitas yang konsisten hingga saat ini ialah Bandung Center of New Media Arts yang menjadi cikal bakal Common Room. Sementara di Yogyakarta, ada MES56 dan Garden of The Blind yang menjadi cikal bakal HONF (The House of Natural Fiber).

Di Jakarta sendiri ada ruangrupa yang pada tahun 2003 menggelar festival seni video pertama di Indonesia. Festival berskala internasional ini diberi tajuk OK. Video – Jakarta Video Art Festival. OK. Video mengetengahkan video secara khusus dan masih rutin digelar setiap dua tahun hingga saat ini.
Penggunaan medium video kemudian semakin marak dan tak hanya terikat pada nilai estetika seni rupa. Farah Wardani, kurator dan penulis seni rupa, menuliskan hasil pengamatannya di Majalah Cobra #2 (Oktober – November, 2011) tentang fenomena yang terjadi di pertengahan 2000 ini. Menurutnya, kala itu video lebih marak dan luas diberdayakan di berbagai jenis komunitas kreatif independen dan LSM. Bentuknya beragam, mulai dari dokumenter, video participatory, video aktivisme seperti yang dilakukan Engagemedia, Forum Lenteng, dan Yayasan Kampung Halaman.
Bukan kebetulan jika pada perhelatan yang kedua, yakni tahun 2005, OK. Video tidak lagi menggunakan kata “art” dan mulai mengusung tema-tema spesifik yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia dan dunia saat itu. Ini bisa kita lihat sebagai usaha OK. Video yang merespon perkembangan yang terjadi saat itu. Sebagai sebuah medium, video terlalu sempit jika hanya dieksplorasi dalam ranah seni rupa saja. Lima tema yang diusung selama enam kali penyelenggaraan festival ini dirasa sesuai untuk setiap zamannya. Saya sendiri pernah terlibat di dua penyelenggaraan OK. Video, yakni OK. Video FLESH (2011) yang mengusung topik ketubuhan dan juga menyinggung tema digital viral, dan MUSLIHAT OK. Video (2013) yang mengetengahkan taktik warga dalam menyiasati teknologi, terutama di negara-negara non-produsen teknologi.
Setiap perhelatannya, OK. Video memilih tiga karya terbaik yang salah satunya berasal dari Indonesia. Selama enam kali penyelenggaraan, video-video yang terpilih cukup jeli membaca tema besar yang disodorkan dan menerapkannya ke dalam video. Tahun lalu, seniman asal Yogyakarta Arya Sukapura Putra dengan karya E-Ruqyah terpilih sebagai salah satu karya terbaik. Ia memberi arti lain pada ritual rukyah dengan menggunakan telepon selular dengan lantunan ayat suci yang menyala untuk digosok-gosokkan ke badannya. Karya video performatif ini dipilih selain karena jenial membaca tema, juga memberi makna baru pada suatu hal yang ada dan telah berlangsung lama.
Praktik seni video yang sedikit berbeda dilakukan oleh komunitas Jatiwangi Art Factory (JAF). Komunitas yang bermarkas di Desa Jatisura, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sejak tahun 2008 bekerjasama dengan Pemerintah Desa Jatisura untuk melakukan berbagai penelitian dengan pendekatan seni kontemporer yang mengajak partisipasi warga desa.
Program-program JAF cukup beragam, seperti lokakarya, proyek kesenian, residensi, dan festival seni. Salah satu program yang menarik perhatian saya ialah pameran bertajuk Pameran Senirupa di Rumah Warga yang diadakan pada September 2013 silam. Sebanyak 16 seniman lokal diundang untuk memamerkan karya mereka di beberapa rumah warga Desa Jatisura. Salah satu seniman video yang terlibat ialah Mahardika Yudha dengan karya Shepherding, Bayangan Timur Laut, Kapal Gersang, dan Suara Putra Brahma. Karya- karya tersebut dipresentasikan menggunakan televisi 29 inch di sebuah rumah warga yang memiliki usaha penyewaan Play Station dan warnet.
Program lain yang juga menarik ialah Village Video Festival (VVF) yang diadakan sejak tahun 2009. Festival video residensi tahunan yang awalnya bernama Village Film Festival ini berskala internasional. Seniman tinggal di rumah warga untuk berinteraksi, memetakan masalah yang ada, dan mengeksekusikannya dengan membuat sebuah karya video. Tahun lalu, VVF mengusung tema “Curi Pandang”. Tema ini dipilih untuk melihat kemungkinan perubahan yang akan terjadi di sekitar wilayah pemukiman mereka. Ini bisa menjadi strategi awal menyiasati pembangunan yang terjadi di sekitar desa mereka.
OK. Video dan JAF memang bukan parameter baku untuk melihat perkembangan seni video di Indonesia saat ini. Namun keduanya pada satu titik menunjukkan kecenderungan serupa, yakni video-video dengan tema yang kontekstual dengan zaman atau lingkungannya dapat membuat “seni video” terasa lebih dekat dan mampu merangkul massa yang lebih luas. Presentasinya pun bisa lebih cair. Video bisa berdiri sendiri sebagai sebuah karya, bisa juga menjadi bagian dari sebuah karya instalasi.
*) Dipublikasikan di majalah Esquire Indonesia edisi Februari 2014